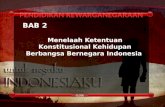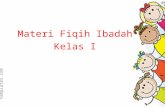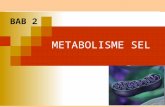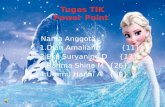Bab 2 Kerosin
-
Upload
shanti-monica -
Category
Documents
-
view
31 -
download
6
Transcript of Bab 2 Kerosin
-
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kerosin dan Avtur
Sebelum mendefinisikan biokerosin, sangat diperlukan kajian tentang karakteristik dari
bahan yang menjadi target penggantian, yaitu kerosin dan avtur. Kerosin dan avtur adalah
campuran hidrokarbon yang tidak berwarna, mudah terbakar, dan memiliki rentang
temperatur pendidihan antara 150oC dan 320oC. Komponen kerosin dan avtur terutama
senyawa-senyawa hidrokarbon parafinik dan naftenik (sikloalkana) dalam rentang C10
sampai C15 dan dispesifikasikan sebanyak 15,9% aromatik, 52,8% naftenik (sikloalkana),
30,8% parafin, dan 0,5% alkena (wikipedia).
Avtur digunakan sebagai bahan bakar mesin jet, sedangkan kerosin banyak digunakan
sebagai bahan bakar memasak di banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Namun,
di beberapa negara lain yang memiliki empat musim, kerosin juga digunakan sebagai
bahan bakar pemanas ruangan.
Tolok ukur terpenting mutu pembakaran kerosin dan avtur adalah titik asap, yakni tinggi
maksimum nyala yang masih bisa dihasilkan, pada lampu standar, tanpa menimbulkan
asap. Kerosin biasanya disyaratkan bertitik asap minimal 16 mm, sedangkan titik beku
kerosin hanya disyaratkan tidak membeku pada temperatur kamar. Avtur, karena
digunakan sebagai bahan bakar mesin jet, titik asapnya disyaratkan minimal 24 mm, dan
titik bekunya maksimal -40oC agar masih dapat mengalir/dipompa ketika pesawat sedang
terbang tinggi. Faktor yang paling berpengaruh pada titik asap kerosin maupun avtur
adalah kadar hidrogen di dalam bahan bakar dan grafik pada Gambar 2.1 [Bridge (1997)]
memperlihatkan kuat dan teraturnya pengaruh tersebut. Sebagai pelengkap, Gambar 2.1
menampilkan pula kadar-kadar hidrogen dalam hidrokarbon-hidrokarbon C10 dan C15.
Alkana (CnH2n+2) biasanya bertitik asap sangat baik/tinggi, sedangkan aromatik (CnH2(n-3))
sangat buruk/rendah. Alkana bercabang, naftena (sikloalkana) dan olefin biasanya adalah
yang optimal : titik asap cukup tinggi, titik beku relatif rendah (Soerawidjaja, 2006).
-
6
Kadar hidrogen (%-b) :
C10H22 : 15,6. C15H32 : 15,2. C10H20 : 14,38. C15H30 : 14,38. C10H18 : 13,13 C15H28 : 13,55. C15H26 : 12,71. C10H16 : 11,85. C15H24 : 11,85.
Gambar 2.1 Hubungan antara kadar hidrogen dengan titik asap kerosin (avtur) dan rumus molekul hidrokarbon C10 C15.
2.2 Biokerosin
Biokerosin adalah bahan bakar cair berasal dari tumbuhan yang memiliki viskositas dan
karakteristik pembakaran mirip kerosin, sehingga dalam penggunaannya tidak
membutuhkan penanganan atau modifikasi pada alat yang menggunakan kerosin sebagai
bahan bakarnya. Dengan demikian, konsumen kerosin akan mendapatkan kenyamanan
dalam menggunakan biokerosin.
Pada umumnya, senyawa hidrokarbon yang sering dijumpai dalam tumbuhan adalah
senyawa hidrokarbon golongan terpen. Kelompok senyawa terpen yang terdapat dalam
rentang hidrokarbon kerosin adalah kelompok monoterpen dan seskuiterpen. Dengan
demikian, tumbuhan-tumbuhan yang berpotensial menjadi sumber biokerosin adalah
tumbuhan-tumbuhan yang mengandung cukup banyak senyawa monoterpen dan
seskuiterpen. Walaupun demikian, monoterpen dan seskuiterpen tidak memiliki kualitas
pembakaran sebaik minyak tanah, karena titik asapnya tidak memenuhi syarat untuk
kerosin. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan cara hidrogenasi untuk
meningkatkan kandungan hidrogen dalam monoterpen dan seskuiterpen, sehingga titik
asapnya dapat ditingkatkan. Dengan cara ini juga, kualitas pembakaran biokerosin dapat
ditingkatkan sampai memenuhi kualitas avtur. Hal ini menunjukkan bahwa selain
biokerosin dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan lokal akan kerosin saat ini,
-
7
biokerosin juga memiliki potensial untuk memenuhi kebutuhan avtur di masa yang akan
datang.
2.2.1 Senyawa Monoterpen
Monoterpen adalah senyawa golongan terpen yang tersusun dari dua senyawa isopren.
Monoterpen memiliki rumus molekul C10H16. Struktur molekul monoterpen dapat berupa
rantai lurus maupun siklik. Monoterpen yang terdapat di dalam pittosporum adalah
myrcene, limonen, pinen, caren, dan sabinen.
Gambar 2.2 Struktur Molekul Mycrene
2.2.2 Senyawa Seskuiterpen
Seskuiterpen adalah senyawa golongan terpen yang tersusun dari tiga senyawa isoprena.
Monoterpen memiliki rumus molekul C15H24. Seperti monoterpen, struktur molekul
seskuiterpen dapat berupa rantai lurus maupun siklik, termasuk banyak struktur
kombinasi yang khas. Contoh dari senyawa seskuiterpen adalah zingiberen, cadinen,
copaen, dan lain-lain.
Gambar 2.3 Struktur Molekul Cadinen
2.3 Tumbuhan Potensial Sumber Biokerosin
Berdasarkan literatur dan hasil penelusuran, tanaman-tanaman yang berpotensial menjadi
sumber biokerosin adalah sebagai berikut,
1. Minyak dari buah pohon Pittosporum sp.,
2. Minyak rinu/kemukus (cubeb oil) dari buah rinu/kemukus (Piper cubeba),
-
8
3. Minyak keruing (gurjun balsam oil), dan
4. Minyak sindur.
Dari keempat tumbuhan di atas, yang paling berpotensial menjadi sumber biokerosin
adalah buah Pittosporum sp. Buah ini menghasilkan minyak yang dapat langsung
digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak tanpa harus diolah lebih lanjut, karena
kualitasnya, baik viskositas maupun titik asapnya, sebanding dengan kerosin. Buah ini
juga yang akan digunakan sebagai bahan baku pada penelitian yang akan dilakukan.
Pada umumnya, tumbuhan anggota keluarga Pittosporum berupa pohon berkayu
berukuran sedang. Yang paling dikenal adalah Pittosporum resiniferum, dengan nama
lokal Hanga dan nama internasional Petroleum nut. Pohon ini banyak terdapat di
Filippina, dan sebagian kecil terdapat di Sulawesi Utara. Sudah sejak lama diketahui
bahwa buah dari pohon ini, yang hijau sekalipun, akan segera terbakar dan menyala
terang jika disulut api. Berbagai penelitian menunjukkan perolehan minyak sebesar 8%
10% dari berat buah dan bahwa minyaknya mengandung n-heptana (5 %), n-nonana (7
%), dan senyawa terpen seperti -pinen (60,2%), camphene (0,1%), sabinene (0,3%), -
pinen (8,9%), mycrene (1,3%), limonen (0,7%), dan sisanya adalah (E)--ocimen, -
caryophyllene, -humulene, germacrene [Bacon (1909), Garcia-Reyes (1937), Salgues
(1954), Nemethy dan Calvin (1982), serta Yaacob dan Ariffin (2000)]. Kehadiran alkana
seperti heptana dan nonana sangat bermanfaat karena meningkatkan mutu bakar (yaitu
titik asap) minyak sebagai pengganti kerosin. Handbook of Energy Crops
(http://www.hort.purdue.edu/newcrop/dukeenergy/Pittosporum_resiniferum.html)
menyatakan bahwa pohon Hanga berpotensi menghasilkan 1 ton minyak per hektar per
tahun. Asian Journal Online (http://asianjournal.com/cgi-bin/ view_info) melaporkan
bahwa Otorita Kelapa dan Kementerian Pertanian Filipina telah menganjurkan
penanaman pohon Hanga di bawah/antara pohon-pohon kelapa.
Berdasarkan penelusuran, tumbuhan anggota keluarga yang banyak terdapat di Indonesia
antara lain, Pittosporum ferrugineum (Ki Honje atau Kacombrangan), Pittosporum
ramiflorum (Wuru combrangan atau Mawuring), dan Pittosporum pentandrum
(Mamelis). Di antara ketiga pohon ini, yang disebutkan di dalam literatur memiliki
kandungan minyak cukup banyak adalah Pittosporum ferrugineum atau Ki Honje [Heyne,
1950]. Buah Ki Honje hanya terdiri atas kulit (berwarna kuning-coklat, 40 % dari berat
-
9
buah) dan biji (berwarna merah, 60 % dari berat buah) dan berdasarkan penelitian yang
telah lalu, baik biji maupun kulitnya mengandung minyak yang berwarna merah.
Gambar 2.4 Foto Buah Ki Honje (termasuk yang muda)
Gambar 2.5 Foto Kulit Buah Ki Honje
Gambar 2.6 Foto Biji Buah Ki Honje
2.4 Pengambilan/Penggondolan dan Uji Nyala Minyak Buah Ki Honje
Pada penelitian sebelumnya (Soerawidjaja,dkk., 2006), biokerosin yang berasal dari buah
Ki Honje diperoleh dengan cara ekstraksi menggunakan alat Soxhlet. Penggondolan
minyak buah Ki Honje juga pernah dilakukan dengan cara distilasi kukus tetapi gagal
memperoleh minyak. Bagian dari buah Ki Honje yang dijadikan bahan baku adalah
-
10
bagian kulit dan bagian bijinya. Perolehan minyak kulit buah Ki Honje dan minyak biji
buah Ki Honje, yang keduanya berwarna merah, setelah diekstraksi adalah sekitar 10 %-
berat dan 12%-berat. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut heksan.
2.4.1 Ekstraksi Padat-Cair Dengan Alat Soxhlet
Ekstraksi merupakan sebuah metode pemisahan yang memanfaatkan kelarutan suatu zat
dalam zat lain. Pada skala laboratorium, ekstraksi padat-cair biasanya dilakukan dengan
menggunakan alat soxhlet. Pada prinsipnya, senyawa hidrokarbon yang terkandung di
dalam buah Ki Honje diambil dengan jalan pengontakan dengan zat pelarut (solvent)
sambil dipanaskan pada titik didih normal pelarut. Skema alat soxhlet diperlihatkan pada
Gambar 2.7.
Keterangan,
1. Pengaduk
2. Labu bundar
3. Jalur uap (distillation path)
4. Selongsong
5. Padatan
6. Siphon top
7. Siphon exit
8. Penghubung
9. Kondensor
10. Air pendingin masuk
11. Air pendingin keluar
Gambar 2.7 Skema Alat Soxhlet
Alat ini didisain untuk mengekstraksi suatu senyawa yang terkandung dalam padatan
dengan menggunakan pelarut (solvent) cairan. Biasanya, Soxhlet digunakan untuk
ekstraksi lipid dari material padatan, namun saat ini Soxhlet juga digunakan untuk
ekstraksi pada lingkup yang luas. Dalam penggondolan minyak buah Ki Honje dengan
menggunakan alat Soxhlet, biji/kulit buah Ki Honje yang akan diekstraksi diletakkan di
dalam sebuah selongsong (nomor 4 pada Gambar 2.7), yang terletak di dalam menara
-
11
utama alat Soxhlet. Kemudian, bagian bawah alat Soxhlet dihubungkan dengan sebuah
labu bundar yang berisi pelarut cair, dan bagian atasnya dihubungkan dengan sebuah
kondensor. Pelarut diuapkan dan uapnya dibawa ke kondensor melalui distilation path
(nomor 3 pada Gambar 2.7). Sebagian uap pelarut akan mengembun di dalam kondensor
dan mengalir ke dalam selongsong dimana terdapat biji/kulit buah Ki Honje di dalamnya.
Semakin lama, selongsong tempat padatan akan terisi oleh pelarut hangat hingga padatan
terendam sepenuhnya oleh pelarut, dan sebagian senyawa yang diinginkan (monoterpen,
seskuiterpen dan heptan), yang terkandung di dalam biji/kulit buah Ki Honje, akan
terlarut ke dalam pelarut. Setelah ketinggian pelarut yang mengisi selongsong lebih tinggi
dari siphon top (nomor 6 pada Gambar 2.7), pelarut akan mengalir kembail ke dalam labu
bundar melalui siphon. Siklus ini terus berulang selama proses ekstraksi berlangsung.
Setelah sekian banyak siklus, maka senyawa yang diinginkan akan terkonsentrasi di
dalam pelarut. Setelah proses ekstraksi selesai, pelarut dipisahkan dengan menggunakan
distilasi. Ekstrak yang diperoleh yaitu minyak biji/kulit buah Ki Honje. Bagian biji/kulit
buah Ki Honje yang tidak terlarut di dalam pelarut tertinggal di dalam selongsong.
2.4.2 Distilasi Kukus
Distilasi kukus adalah metode distilasi khusus untuk memisahkan material yang sensitif
terhadap temperatur seperti senyawa aromatik organik. Metode ini menggunakan prinsip
bahwa tekanan total dari suatu campuran yang tidak saling larut merupakan penjumlahan
dari tekanan uap masing-masing komponennya. Jika tekanan total sama dengan tekanan
atmosfer, maka campuran tersebut akan mendidih. Dengan demikian, campuran memiliki
titik didih yang lebih rendah dari titik didih komponen-komponennya. Berdasarkan fakta
tersebut, penambahan uap air akan menyebabkan senyawa organik yang terkandung di
dalam bahan baku teruapkan pada temperatur yang lebih rendah dari titik didihnya.
Setelah disitilasi, uap yang dihasilkan akan terkondensasi di dalam kondensor dan
kondensat ditampung terlebih dulu di dalam dekanter sebelum diambil. Di dekanter akan
dihasilkan sistem dua fasa, yakni fasa air dan fasa senyawa organik. Dengan demikian,
pemisahan selanjutnya untuk memperoleh senyawa organik dapat dilakukan dengan
mudah. Skema alat distilasi diperlihatkan pada Gambar 2.8.
-
12
Gambar 2.8 Skema Alat Distilasi Kukus
2.4.3 Uji Nyala Minyak Buah Ki Honje
Pengujian yang pernah dilakukan adalah pengujian dengan menggunakan lampu minyak
sederhana. Kemudian, diamati dan dibandingkan kualitas nyala apinya dengan kerosin.
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, secara kualitatif, kualitas nyala api dari
minyak buah Ki Honje lebih baik dibandingkan dengan kualitas nyala api dari kerosin.
Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa kualitas nyala api dari minyak buah
Ki Honje lebih baik dari nyala api dari minyak tanah,
Gambar 2.9 Uji pembandingan nyala api kerosin (kiri) dengan nyala api minyak kulit
buah Ki Honje (kanan)
-
13
Gambar 2.10 Uji pembandingan nyala api kerosin (kiri) dengan nyala api minyak biji
buah Ki Honje (kanan)
Gambar 2.9 dan 2.10 mengisyaratkan bahwa minyak buah Ki Honje sangat berpotensial
untuk menggantikan kerosin. Dengan kualitas nyala yang lebih baik, maka penggunaan
minyak buah Ki Honje akan menjadi lebih hemat dan lebih efisien dari pada penggunaan
kerosin. Namun, pengujian lebih lanjut, meliputi standar kualitas, perlu dilakukan agar
minyak buah Ki Honje dapat menggantikan kerosin.
2.5 Penelitian Lebih Lanjut Tentang Biokerosin
2.5.1 Pengaruh Pemilihan Pelarut Pada Ekstraksi Minyak Buah Ki Honje
Terhadap Titik Asap
Pada penelitian sebelumnya oleh Soerawidjaja dan mahasiswanya (2006), ekstraksi buah
Ki Honje dilakukan dengan menggunakan pelarut heksan. Dari uji nyala yang telah
dilakukan, terdapat kemungkinan terkandungnya senyawa heptan dalam minyak buah Ki
Honje, yang menjadikan minyak Ki Honje memiliki titik asap yang memuaskan. Oleh
karena itu, dengan penggunaan pelarut heksan akan mempengaruhi kualitas minyak buah
Ki Honje.
Heksan memiliki titik didih normal 69 oC, sedangkan heptan memiliki titik didih normal
98,4 oC. Saat proses ekstraksi selesai, maka dilanjutkan dengan proses pemisahan pelarut,
yakni dengan cara menguapkan pelarut dan menyisakan senyawa ekstrak. Karena
dekatnya titik didih heksan, sebagai pelarut, dengan heptan yang terkandung dalam
minyak buah Ki Honje, maka terdapat kemungkinan teruapkannya heptan saat proses
-
14
pemisahan pelarut berlangsung. Dengan demikian, titik asap minyak buah Ki Honje akan
berkuarang dari yang seharusnya karena berkurangnya jumlah heptan. Penelitian lebih
lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas sebenarnya minyak
buah Ki Honje. Oleh karena itu, penggunaan pelarut lain yang memiliki titik didih yang
jauh lebih rendah dari titik didih heptan perlu dipertimbangkan. Selain heksan, pelarut
yang berpotensial untuk digunakan dalam estraksi minyak buah Ki Honje adalah
dikhlorometana (T.d. 39,8 oC), dietil eter (T.d 34,6 oC), dan aseton (T.d. 56,5 oC).
2.5.2 Uji Titik Asap dan Titik Beku Minyak Buah Ki Honje
Seperti yang didefinisikan sebelumnya, bahwa biokerosin adalah bahan bakar minyak
dari tumbuhan yang memiliki karakteristik mirip kerosin, maka perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut mengenai karakteristik minyak buah Ki Honje, untuk membuktikan bahwa
minyak buah Ki Honje memiliki karakteristik mirip minyak tanah. Dengan demikian,
dapat diketahui bahwa minyak buah Ki Honje memiliki prospek ke depan untuk
menggantikan minyak tanah tanpa harus mengubah cara penggunaannya, yaitu
menggunakan kompor minyak biasa (yang sudah ada/dimiliki konsumen). Selain itu,
dengan biaya produksi yang tidak terlalu mahal, minyak buah Ki Honje dapat dibeli
konsumen dengan harga lebih murah. Pengujian karakteristik minyak buah Ki Honje
yang akan dilakukan meliputi, pengujian titik asap dan pengujian titik beku.
Pengujian titik asap merupakan parameter penting yang menunjukkan bahwa minyak
buah Ki Honje memiliki kualitas bakar yang setara dengan minyak tanah. Untuk hasil
yang lebih teliti, pengujian titik asap akan dilakukan dengan metode standar, yaitu ASTM
D1322 menggunakan lampu titik asap. Sampel minyak dibakar di dalam lampu dan
diukur tinggi api tanpa menyebabkan asap (prosedur pengujian dapat dilihat di Lampiran
B).
Pengujian titik beku dilakukan untuk mengetahui potensial minyak buah Ki Honje untuk
dijadikan bioavtur, karena syarat avtur harus memiliki titik beku maksimal -40oC agar
masih dapat mengalir/dipompa ketika pesawat sedang terbang tinggi. Pengujian
dilakukan juga dengan menggunakan metode standar, yaitu ASTM D2386 (prosedur
pengujian dapat dilihat di Lampiran B).
-
15
Gambar 2.11 Lampu Uji Titik Asap (ASTM D1322)
Gambar 2.12 Alat Uji Titik Beku (ASTM D2386)