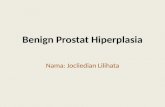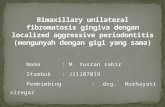ASUHAN KEPERAWATAN HIPERPLASIA PROSTAT .doc
-
Upload
evi-dwi-indriyani -
Category
Documents
-
view
44 -
download
1
Transcript of ASUHAN KEPERAWATAN HIPERPLASIA PROSTAT .doc

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Lanjut usia (Lansia), pada umumnya mengalami perubahan-perubahan
pada jaringan tubuh, yang disebabkan proses degenerasi, terjadi terutama pada
organ-organ tubuh, dimana tidak ada lagi perkembangan sel seperti otot,
jantung dan ginjal tetapi kurang pada organ-organ dimana masih ada mitosis
seperti hepar. Proses degenerasi menyebabkan perubahan kemunduran fungsi
organ tersebut, termasuk juga sistem traktus urinarius, sehingga menyebabkan
macam-macam kelainan atau penyakit urologis tertentu (Dharmojo &Martono,
2000). Dengan menuanya seorang pria, kelenjar prostatnya membesar, sekresi
prostat menurun, skrotum menggantung lebih rendah, testis menjadi lebih kecil
dan lebih keras, dan rambut pubis menjadi lebih jarang dan lebih kaku.
Inkontinensia urin pada lansia pria mempunyai banyak penyebab termasuk
medikasi dan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan usia, seperti penyakit
neurologi atau hyperplasia prostat jinak (Brunner & Suddarth, 2001).
Kelenjar prostat adalah organ tubuh pria yang paling sering mengalami
pembesaran, baik jinak maupun ganas. Pembesaran prostat jinak atau Benign
Prostatic Hiperplasia yang selanjutnya disingkat BPH merupakan penyakit
tersering kedua penyakit kelenjar prostat di klinik urologi di Indonesia.
Kelenjar periuretra mengalami pembesaran, sedangkan jaringan prostat asli
terdesak ke perifer menjadi kapsul. BPH akan timbul seiring dengan
bertambahnya usia, sebab BPH erat kaitannya dengan proses penuaan (Birowo,
2002).
Fungsi kandung kemih dan uretra pada manula dipengaruhi proses
fisiologis penuaan pada beberapa sistem. Kontrol serebral dari miksi
dipengaruhi oleh atrofi yang progresif pada korteks serebri dan neuron. Fungsi
otonom juga lambat laun menurun menyebabkan refleks otonom terganggu.
Misalnya dapat dilihat pada anatomi kandung kencing. Penuaan ditandai
dengan kurangnya jumlah sel-sel otot dan digantikan oleh jaringan lemak dan
jaringan ikat. Jaringan otot ini dapat berkurang sampai setengah pada umur 80
1

tahun, yang dapat menyebabkan kontraksi melemah (Nursalam dan Fransisca,
2009).
Sistem genitourinaria tetap berfungsi secara adekuat pada individu lansia,
meskipun terjadi penurunan massa ginjal akibat kehilangan primer beberapa
nefron. Perubahan fungsi ginjal meliputi penurunan laju filtrasi, penurunan
fungsi tubuler dengan penurunan efisiensi dalam resorbsi dan pemekatan urin,
dan perlambatan restorasi keseimbangan asam basa terhadap stress. Ureter,
kandung kemih menurun dan lansia tidak mampu lagi mengosongkan kandung
kemihnya secara sempurna. Retensi urin yang terjadi akan meningkatkan
resiko infeksi. Sering berkemih, dorongan dan inkontinensia juga merupakan
masalah yang biasa (Brunner & Suddarth, 2001).
Penelitian secara histopatologis di negara barat menunjukkan sekitar 20 %
kasus BPH pada umur 41-50 tahun, 50% pada umur 51-60 tahun, dan lebih
dari 90% pada umur lebih dari 80 tahun. Di indonesia BPH merupakan
kelainan urologi kedua setelah batu saluran kemih yang dijumpai di klinik
urologi dan diperkirakan 50% pada pria berusia di atas 50 tahun. Angka
harapan hidup di Indonesia, rata-rata mencapai 65 tahun sehingga diperkirakan
2,5 juta laki-laki di Indonesia menderita BPH (Pakasi, 2009).
Hyperplasia prostat benigna merupakan temuan yang sering pada pria
lansia. Pembesaran prostat menyebabkan retensi urin kronis, sering berkemih
dan inkontinensia (Brunner & Suddarth, 2001). Pada banyak pasien dengan
usia diatas 50 tahun, kelenjar prostatnya mengalami pembesaran, memanjang
keatas ke dalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan menutupi
orifisium uretra. Kondisi ini dikenal sebagai hyperplasia prostatik jinak (BPH),
perbesaran, atau hipertrofi prostat. BPH adalah kondisi patologis yang paling
umum pada pria lansia dan penyebab kedua yang paling sering untuk intervensi
medis pada pria diatas usia 60 tahun (Brunner & Suddarth, 2001).
Penyebab BPH belum diketahui secara pasti, tetapi sampai saat ini
berhubungan dengan proses penuaan yang mengakibatkan penurunan kadar
hormon pria, terutama testosteron. Perubahan mikroskopik pada prostat telah
terjadi pada pria usia 30-40 tahun. Bila perubahan mikroskopik ini
berkembang, akan terjadi perubahan patologik anatomi yang ada pada pria usia
2

50 tahun angka kejadiannya sekitar 50%, usia 80 tahun sekitar 80%, dan usia
90 tahun 100%. Insiden di negara berkembang meningkat karena adanya
peningkatan usia harapan hidup (Mansjoer, 2002).
Pembesaran kelenjar prostat mempunyai angka morbiditas yang bermakna
pada popilasi pria lanjut usia. Gejalanya merupakan keluhan yang umum dalam
bidang bedah urologi. Hiperplasia prostat merupakan salah satu masalah
kesehatan utama bagi pria di atas usia 50 tahun dan berperan dalam penurunan
kualitas hidup seseorang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa sepertiga dari
pria berusia antara 50-79 tahun mengalami hiperplasia prostat. Adanya
hiperplasia ini akan menyebabkan terjadinya obstruksi saluran kemih dan
untuk mengatasi obstruksi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari
tindakan yang paling ringan yaitu secara konservatif (non operatif) sampai
tindakan yang paling berat yaitu operasi (Nursalam dan Fransisca, 2009).
2. Tujuan
a. Tujuan Umum
Mengetahui konsep dasar penyakit Benigna Hyperplasia Prostat dan asuhan
keperawatan yang dapat ditegakkan pada klien lansia.
b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penyusunan makalah ini adalah :
1) Mengetahui pengertian, etiologi, faktor pencetus, patofisiologi, tanda
dan gejala, pemeriksaan penunjang, dan penatalaksanaan hyperplasia
prostat pada lansia
2) Dapat melakukan pengkajian pada klien lansia dengan hyperplasia
prostat
3) Mendeskripsikan diagnosa yang mungkin muncul pada klien lansia
dengan hyperplasia prostat
4) Membuat rencana asuhan keperawatan meliputi tujuan dan kriteria
hasil, intervensi dan rasional pada klien lansia dengan hyperplasia
prostat.
3

B. TINJAUAN TEORI
1. Pengertian
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) atau disebut tumor prostat jinak adalah
pertumbuhan berlebihan dari sel-sel prostat yang tidak ganas. Pembesaran
prostat jinak akibat sel-sel prostat memperbanyak diri melebihi kondisi normal,
biasanya dialami laki-laki berusia di atas 50 tahun (Price, 2006).
2. Etiologi
BPH adalah tumor jinak pada pria yang paling sering ditemukan. Pria berumur
lebih dari 50 tahun, kemungkinannya memiliki BPH adalah 50%. Ketika
berusia 80–85 tahun, kemungkinan itu meningkat menjadi 90%. Beberapa teori
telah dikemukakan berdasarkan faktor histologi, hormon, dan faktor perubahan
usia, di antaranya :
a. Teori DHT (dihidrotestosteron). Testosteron dengan bantuan enzim 5-α
reduktase dikonversi menjadi DHT yang merangsang pertumbuhan kelenjar
prostat.
b. Teori Reawakening. Teori ini berdasarkan kemampuan stroma untuk
merangsang pertumbuhan epitel.
c. Teori stem cell hypotesis. Stem sel akan berkembang menjadi sel aplifying.
Sel aplifying akan berkembang menjadi sel transit yang tergantung secara
mutlak pada androgen, sehingga dengan adanya androgen sel ini akan
berproliferasi dan menghasilkan pertumbuhan prostat yang normal.
d. Teori growth factors. Faktor pertumbuhan ini dibuat oleh sel-sel stroma di
bawah pengaruh androgen. Adanya ekspresi berlebihan dari epidermis
growth factor (EGF) dan atau fibroblast growth factor (FGF) dan atau
adanya penurunan ekspresi transforming growth factor-β (TGF-β), akan
menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan prostat dan
menghasilkan pembesaran prostat.
(Birowo, 2002).
3. Faktor Predisposisi/Faktor Pencetus
4

a. Kadar Hormon
Kadar hormon testosteron yang tinggi berhubungan dengan peningkatan
risiko BPH.
b. Usia
Pada usia tua terjadi kelemahan umum termasuk kelemahan pada buli (otot
detrussor) dan penurunan fungsi persarafan.
c. Riwayat keluarga
Bila salah satu anggota keluarga menderita BPH, maka risiko meningkat 2
kali bagi anggota keluarga yang lain.
d. Obesitas
Pada obesitas terjadi peningkatan kadar estrogen yang berpengaruh
terhadap pembentukan BPH melalui peningkatan sensitiasi prostat terhadap
androgen dan menghambat proses kematian sel-sel kelenjar prostat.
e. Pola diet
Kekurangan mineral penting seperti seng, tembaga, selenium berpengaruh
pada fungsi reproduksi pria. Yang paling penting adalah seng, karena
defisiensi seng berat dapat menyebabkan pengecilan testis yang selanjutnya
berakibat penurunan kadar testosteron. Selain itu, makanan tinggi lemak
dan rendah serat juga mengakibatkan penurunan kadar testosteron.
f. Aktivitas seksual
BPH dihubungkan dengan kegiatan seks berlebihan dan alasan kebersihan.
Saat kegiatan seksual, kelenjar prostat mengalami peningkatan tekanan
darah sebelum terjadi ejakulasi. Jika suplai darah ke prostat selalu tinggi,
akan terjadi hambatan prostat yang mengakibatkan kelenjar tersebut
bengkak permanen.
g. Kebiasaan merokok
Nikotin dan konitin (produk pemecahan nikotin) pada rokok meningkatkan
aktivitas enzim perusak androgen, sehingga menyebabkan penurunan kadar
testosteron.
h. Kebiasaan minum-minuman beralkohol
Konsumsi alkohol akan menghilangkan kandungan zink dan vitamin B6
yang penting untuk prostat yang sehat.
5

i. Olahraga
Dengan olahraga, kadar dehidrotestosteron dapat diturunkan sehingga dapat
memperkecil resiko gangguan prostat. Selain itu, olahraga akan mengontrol
berat badan agar otot lunak yang melingkari prostat tetap stabil.
j. Penyakit diabetes melitus
Laki-laki dengan penyakit diabetes melitus mempunyai resiko dua kali
terjadi BPH dibandingkan dengan laki-laki dengan kondisi normal.
(Amalia, 2010).
4. Patofisiologi
Kelenjar prostat adalah salah satu organ genitalia pria yang terletak di
sebelah inferior buli-buli, dan membungkus uretra posterior. Pada usia lanjut,
akan terjadi perubahan keseimbangan testosteron estrogen karena produksi
testosteron menurun dan terjadi konversi testosteron menjadi estrogen pada
jaringan adipose di perifer. Pertumbuhan kelenjar prostat ini sangat tergantung
pada hormon testosteron, yang di dalam sel-sel kelenjar prostat hormon ini
akan dirubah menjadi dehidrotestosteron (DHT) dengan bantuan enzim alfa
reduktase. Dehidrotestosteron inilah yang secara langsung memacu m-RNA di
dalam sel-sel kelenjar prostat untuk mensisntesis protein sehingga terjadi
pertumbuhan kelenjar prostat.
Perubahan paling awal pada BPH adalah di kelenjar periuretra sekitar
verumontanum :
a. Perubahan hiperplasia pada stroma berupa nodul fibromuskuler, nodul
asinar atau nodul campuran fibroadenomatosa.
b. Hiperplasia glandular terjadi berupa nodul asinar atau campuran dengan
hiperplasia stroma. Kelenjar-kelenjar biasanya besar dan terdiri atas tall
columnar cells. Inti sel-sel kelenjar tidak menunjukkan proses keganasan.
(Birowo, 2002).
Oleh karena pembesaran prostat terjadi perlahan, maka efek terjadinya
perubahan pada traktus urinarius juga terjadi perlahan-lahan. Perubahan
patofisiologis yang disebabkan pembesaran prostat disebabakan oleh
kombinasi resistensi uretra daerah prostat, tonus trigonum, leher vesika, dan
6

kekuatan otot detrussor. Detrussor dipersarafi oleh saraf parasimpatis,
sedangkan trigonum, leher vesika dan prostat dipersarafi oleh saraf simpatis.
Pada tahap awal setelah terjadinya pembesaran prostat akan terjadi resistensi
yang bertambah pada leher vesika dan daerah prostat. Kemudian detrussor
akan mencoba mengatasi keadaan ini dengan jalan kontraksi lebih kuat dan
detrussor menjadi lebih tebal. Fase penebalan detrussor ini disebut fase
kompensasi otot dinding kandung kemih. Apabila keadaan berlanjut maka
detrussor menjadi lelah dan akhirnya mengalami dekompensasi dan tidak
mampu lagi untuk berkontraksi sehingga terjadi retensi urine (Sjamsuhidajat,
2004).
Karena produksi urine terus terjadi, maka suatu saat vesika urinaria tidak
mampu lagi menampung urin, sehingga terjadi tekanan intravesikel lebih tinggi
dari tekanan sfingter dan obstruksi sehingga terjadi inkontinensia paradox
(overflow incontinence). Retensi kronik menyebabkan refluks vesika ureter dan
dilatasi ureter dan ginjal, maka ginjal akan rusak dan terjadi gagal ginjal.
Kerusakan traktus urinarius bagian atas akibat dari obstruksi kronik
mengakibatkan penderita harus mengejan saat miksi yang menyebabkan
peningkatan tekanan intraabdomen yang akan menimbulkan hernia atau
hemoroid. Karena selalu terdapat sisa urin, dapat terdapat batu endapan di
dalam kandung kemih. Batu ini dapat menambah keluhan iritasi dan
menimbulkan hematuria. Batu tersebut dapat pula menyebabkan sistitis dan
bila terjadi refluks, dapat terjadi pielonefritis (Sjamsuhidajat, 2004).
5. Tanda dan Gejala
Biasanya gejala-gejala pembesaran prostat jinak, dikenal sebagai Lower
Urinary Tract Symptomps (LUTS), dibedakan menjadi gejala iritatif dan
obstruktif.
a. Gejala Iritatif yaitu :
1) Sering miksi
2) Terbangun untuk miksi pada malam hari (nokturia)
3) Perasaan ingin miksi yang sangat mendesak (urgensi)
4) Nyeri pada saat miksi (disuria)
7

b. Gejala obstruktif yaitu :
1) Pancaran lemah
2) Rasa ingin kencing lagi sesudah kencing (double voiding)
3) Harus menunggu lama bila hendak miksi (hesitancy)
4) Harus mengedan (strainning)
5) Kencing terputus-putus (intermittency)
6) Waktu miksi memanjang yang akhirnya menjadi retensio urin dan
inkontinensia karena overflow.
(Mansjoer, 2002).
Tanda klinis terpenting dalam BPH adalah ditemukannya pembesaran
pemeriksaan pada pemeriksaan colok dubur atau Digital Rectal Examination
(DRE). Pada BPH, prostat teraba membesar dengan konsistensi kenyal
(Mansjoer, 2000).
Keluhan ini biasanya disusun dalam bentuk skor simptom. Terdapat
jenis klasifikasi yang dapat digunakan untuk membantu diagnosis dan
menentukan tingkat beratnya penyakit, diantaranya adalah skor internasional
gejala-gejala prostat WHO (International Prostate Symptomp Score, IPPS) dan
skor Madsen Iversen. Gejala dan tanda pada pasien yang telah lanjut
penyakitnya, misalnya gagal ginjal, dapat ditemukan uremia, peningkatan
tekanan darah, denyut nadi, respirasi, foeter uremik, perikarditis, ujung kuku
yang pucat, tanda-tanda penurunan mental serta neuropati perifer. Bila sudah
terjadi hidronefrosis tau pionefrosis, ginjal teraba dan ada nyeri di CVA (Costo
Vertebrae Angularis) (Mansjoer, 2000).
6. Pemeriksaan Penunjang
a. Pemeriksaan Laboratorium
Darah : Ureum, kreatinin, elektrolit, Blood urea nitrogen, Prostate
Specific Antigen (PSA), Gula darah.
b. Urine : Kultur urin dan test sensitifitas, urinalisis dan pemeriksaan
mikroskopis, sedimen.
c. Pemeriksaan pencitraan
1) Foto polos abdomen (BNO)
8

Dari sini dapat diperoleh keterangan mengenai penyakit ikutan
misalnya batu saluran kemih, hidronefrosis, atau divertikel kandung
kemih juga dapat untuk mengetahui adanya metastasis ke tulang dari
carsinoma prostat.
2) Pielografi Intravena (IVP)
Pembesaran prostat dapat dilihat sebagai filling defect/indentasi
prostat pada dasar kandung kemih atau ujung distal ureter membelok
keatas berbentuk seperti mata kail (hooked fish). Dapat pula
mengetahui adanya kelainan pada ginjal maupun ureter berupa
hidroureter ataupun hidronefrosis serta penyulit (trabekulasi,
divertikel atau sakulasi buli – buli). Foto setelah miksi dapat dilihat
adanya residu urin.
3) Cystogram retrograde
Memberikan gambaran indentasi pada pasien yang telah dipasang
kateter karena retensi urin.
4) Transrektal Ultrasonografi (TRUS)
Deteksi pembesaran prostat dengan mengukur residu urin.
5) MRI atau CT scan
Jarang dilakukan. Digunakan untuk melihat pembesaran prostat dan
dengan bermacam – macam potongan.
(Mansjoer, 2000).
9

7. Pathway
Perubahan usia (usia lanjut)
Ketidakseimbangan produksi estrogen dan testosteron
Kadar testosteron menurun Kadar estrogen meningkat
Proliferasi sel prostat Hiperplasia sel stroma pada jaringan prostat
Obstruksi saluran kemih BPH Pembedahan
Kompensasi Dekompensasi Perdarahan Terputusnya Otot detrussor otot detrussor kontinuitas
jaringan
Spasme otot Penebalandetrussor dinding urinaria
Otot suprapubik Kontraksi otot
Kesulitan berkemih
Dipasang kateter
10
Nyeri akut
Resiko infeksi
Retensi urine
Risiko Kekurangan
volume cairanNyeri akut
Cemas Disfungsi seksual

8. Penatalaksanaan
Penatalaksanaan BPH berupa :
a. Watchful Waiting
Watchful waiting dilakukan pada penderita dengan keluhan ringan.
Tindakan yang dilakukan adalah observasi saja tanpa pengobatan.
b. Terapi Medikamentosa
Pilihan terapi non-bedah adalah pengobatan dengan obat
(medikamentosa).
c. Terapi Bedah Konvensional
Open simple prostatectomy
Indikasi untuk melakukan tindakan ini adalah bila ukuran prostat terlalu
besar, di atas 100g, atau bila disertai divertikulum atau batu buli-buli.
d. Terapi Invasif Minimal
1) Transurethral resection of the prostate (TUR-P)
Menghilangkan bagian adenomatosa dari prostat yang menimbulkan
obstruksi dengan menggunakan resektoskop dan elektrokauter.
2) Transurethral incision of the prostate (TUIP)
Dilakukan terhadap penderita dengan gejala sedang sampai berat dan
dengan ukuran prostat kecil.
e. Terapi laser
Tekniknya antara lain Transurethral laser induced prostatectomy (TULIP)
yang dilakukan dengan bantuan USG, Visual coagulative necrosis, Visual
laser ablation of the prostate (VILAP), dan interstitial laser therapy.
f. Terapi alat
1) Microwave hyperthermia
Memanaskan jaringan adenoma melalui alat yang dimasukkan melalui
uretra atau rektum sampai suhu 42-45oC sehingga diharapkan terjadi
koagulasi.
2) Trans urethral needle ablation (TUNA)
Alat yang dimasukkan melalui uretra yang apabila posisi sudah diatur,
dapat mengeluarkan 2 jarum yang dapat menusuk adenoma dan
11

mengalirkan panas, sehingga terjadi koagulasi sepanjang jarum yang
menancap di jaringan prostat.
3) High intensity focused ultrasound (HIFU)
Melalui probe yang ditempatkan di rektum yang memancarkan energi
ultrasound dengan intensitas tinggi dan terfokus.
4) Intraurethral stent
Adalah alat yang secara endoskopik ditempatkan di fosa prostatika
untuk mempertahankan lumen uretra tetap terbuka.
5) Transurethral baloon dilatation
Dilakukan dengan memasukkan kateter yang dapat mendilatasi fosa
prostatika dan leher kandung kemih.
(Birowo, 2002)
9. Pengkajian
a. Identitas Klien
Nama, umur, alamat, pendidikan, jenis kelamin, suku, agama, status
perkawinan, tanggal pengkajian.
b. Status kesehatan saat ini
Kaji keluhan utama saat ini meliputi awitan, durasi, kualitas dan
karakteristik, lokasi dari gejala hiperplasia prostat.
Gejala Iritatif :
Sering miksi, terbangun untuk miksi pada malam hari (nokturia), perasaan
ingin miksi yang sangat mendesak (urgensi), nyeri pada saat miksi
(disuria)
Gejala obstruktif :
Pancaran lemah, rasa ingin kencing lagi sesudah kencing (double
voiding), harus menunggu lama bila hendak miksi (hesitancy), harus
mengedan (strainning), kencing terputus-putus (intermittency), waktu
miksi memanjang.
c. Riwayat Kesehatan dahulu
1) Kaji riwayat penyakit lain dan penyakit pada saluran urogenitalia
(pernah mengalami cedera, infeksi, atau pembedahan).
12

2) Obat-obatan yang saat ini dikonsumsi yang dapat menimbulkan
keluhan miksi.
3) Kaji faktor risiko seperti : obesitas, pola diet, aktivitas seksual,
kebiasaan merokok, kebisaan minum alkohol, olahraga, penyakit
diabetes melitus.
d. Riwayat kesehatan keluarga
Kaji ada tidaknya anggota keluarga yang menderita BPH.
e. Pemeriksaan Fisik
1) Pemeriksaan tekanan darah, nadi, dan suhu.
2) Pemeriksaan abdomen pada daerah suprapubik
Inspeksi : penonjolan pada daerah suprapubik
Palpasi : kandung kencing terisi penuh, klien akan terasa ingin miksi,
nyeri tekan supra simfisis.
Perkusi : Dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya residual urin.
3) Pemeriksaan penis dan uretra untuk mendeteksi kemungkinan striktur
uretra, batu uretra, karsinoma.
4) Pemeriksaan scrotum untuk menentukan adanya epididimitis
5) Rectal touch / pemeriksaan colok dubur brtujuan untuk menentukan
konsistensi besarnya prostat.
Pemeriksaan colok dubur dapat memberikan gambaran tentang
keadaan tonus spingter ani, reflek bulbo cavernosus, mukosa rektum,
adanya kelainan lain seperti benjolan di dalam rektum. Pada perabaan
prostat harus diperhatikan :
Konsistensi prostat (pada hiperplasia prostat konsistensinya kenyal),
Adakah asimetris, Adakah nodul pada prostate, Apakah batas atas
dapat diraba, Sulcus medianus prostate, Adakah krepitasi
f. Tinjuan sistem
1) Sirkulasi
Tanda : Peningkatan tekanan darah
2) Integritas ego
Kaji tanda-tanda seperti kegelisahan, kacau mental, perubahan
perilaku.
13

3) Nutrisi/cairan
Kaji anoreksia, mual, muntah, penurunan berat badan.
4) Nyeri/kenyamanan
Kaji nyeri suprapubis, panggul, atau punggung.
5) Keamanan
Kaji faktor keselamatan.
6) Seksualitas
Kaji Gejala meliputi : efek kondisi kemampuan seksual, takut
inkontinensia/menetes selama hubungan intim, penurunan kekuatan
kontraksi ejakulasi.
g. Pemeriksaan laboratorium
1) Pemeriksaan darah lengkap, faal ginjal, serum elektrolit, dan kadar
gula digunakan untuk memperoleh data dasar keadaan umum klien.
2) Pemeriksaan urin lengkap dan kultur.
3) PSA (Prostatic Spesific Antigen) penting diperiksa sebagai
kewaspadaaan adanya keganasan.
10. Diagnosa yang mungkin muncul
Pre operasi
a. Retensi urine berhubungan dengan pembesaran prostat, dekompensasi otot
detrussor.
b. Nyeri akut berhubungan dengan iritasi mukosa, distensi kandung kemih.
c. Resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan paparan lingkungan
terhadap patogen (pemasangan kateter).
d. Ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan, menghadapi
prosedur bedah.
Post operasi
e. Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera biologi (terputusnya
kontinuitas jaringan akibat pembedahan).
14

f. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif : alat selama
pembedahan.
g. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan pascaobstruksi diuresis.
h. Risiko tinggi disfungsi seksual berhubungan dengan sumbatan saluran
ejakulasi, hilangnya fungsi tubuh.
11.Rencana Asuhan Keperawatan
No Diagnosa Kriteria Hasil Intervensi Rasional
1. Retensi urine
berhubungan dengan
pembesaran prostat,
dekompensasi otot
detrussor.
Tujuan :
Setelah dilakukan
perawatan
selama....x 24 jam
retensi urin pasien
teratasi.
Kriteria Hasil :
a.Kandung kemih
kosong secara
penuh.
b.Tidak ada residu
urine >100-200
cc.
c.Intake cairan
dalam rentang
normal.
d.Bebas dari ISK.
e.Tidak ada spasme
bladder.
f. Balance cairan
seimbang.
a. Monitor intake
dan output.
b. Monitor derajat
distensi blader.
c. Stimulasi
refleks bladder
dengan kompres
dingin pada
abdomen.
d. Dorong pasien
untuk berkemih
setiap 2-4 jam.
e. Observasi aliran
Membantu
mengidentifikasi
pengeluaran urine
dan kebutuhan
cairan.
Meminimalkan
retensi urin.
Meningkatkan
relaksasi otot,
penurunan edema,
dan dapat
meningkatksn
upaya berkemih.
Meminimalkan
retensi urin dan
distensi berlebihan
pada kandung
kemih.
Berguna untuk
15

urine,
perhatikan
ukuran dan
kekuatan.
f. Awasi dan catat
waktu dan
jumlah setiap
kali berkemih.
mengevaluasi
obstruksi dan
pilihan intervensi.
Retensi urine
meningkatkan
tekanan dalam
saluran perkemihan
atas, yang dapat
mempengaruhi
fungsi ginjal.
2. Nyeri akut
berhubungan dengan
iritasi mukosa,
distensi kandung
kemih.
Tujuan :
Setelah dilakukan
perawatan selama
...x 24 jam nyeri
klien berkurang atau
hilang.
Kriteria Hasil :
a. Mampu
mengontrol
nyeri
(mengetahui
penyebab nyeri,
mampu
menggunakan
tehnik
nonfarmakologi
untuk
mengurangi
nyeri).
b. Me
a. Lakukan
pengkajian nyeri
secara
komprehensif
termasuk lokasi,
karakteristik,
durasi,
frekuensi,
kualitas dan
faktor
presipitasi.
b. Berikan
informasi
mengenai nyeri
klien meliputi
penyebab nyeri
dan intensitas
nyeri.
Untuk mengetahui
sejauh mana
perkembangan rasa
nyeri yang
dirasakan oleh
klien sehingga
dapat dijadikan
sebagai acuan
untuk intervensi
selanjutnya.
Membantu klien
dalam mengontrol
nyeri.
16

laporkan bahwa
nyeri berkurang.
c. Ta
nda vital dalam
rentang normal.
d. Tid
ak mengalami
gangguan tidur.
c. Observasi reaksi
nonverbal dari
ketidaknyamana
n.
d. Kontrol
lingkungan yang
dapat
mempengaruhi
nyeri seperti
suhu ruangan,
pencahayaan
dan kebisingan.
e. Ajarkan klien
teknik non
farmakologi :
napas dalam,
relaksasi.
f. Anjurkan klien
untuk
menggunakan
rendam duduk.
Untuk mengetahui
tingkat
ketidaknyamanan
klien.
Mengurangi faktor
presipitasi nyeri.
Meningkatkan
relaksasi,
memfokuskan
kembali perhatian,
dan dapat
meningkatkan
kemampuan
koping.
Menigkatkan
relaksasi otot.
3. Resiko infeksi
berhubungan dengan
peningkatan paparan
lingkungan terhadap
patogen (pemasangan
Tujuan :
Setelah dilakukan
perawatan selama
...x 24 jam klien
tidak mengalami
a. Pertahankan
teknik aseptif.
b. Monitor tanda
Menurunkan resiko
kontaminasi
bakteri.
Membantu deteksi
17

kateter). infeksi.
Kriteria Hasil :
a. Klien bebas dari
tanda dan gejala
infeksi.
b. Menunjukkan
kemampuan
untuk mencegah
timbulnya
infeksi
dan gejala
infeksi sistemik
dan lokal.
c. Inspeksi kulit
dan membran
mukosa
terhadap
kemerahan,
panas, drainase.
d. Ajarkan pasien
dan keluarga
mengenai tanda
dan gejala
infeksi.
dini terjadinya
infeksi.
Membantu deteksi
terjadinya infeksi.
Membantu
mengontrol resiko
terjadinya infeksi.
4. Ansietas berhubungan
dengan perubahan
status kesehatan,
menghadapi prosedur
bedah.
Tujuan :
Setelah dilakukan
perawatan selama
...x 24 jam klien
mampu mengatasi
ansietas.
Kriteria Hasil :
a. Klien mampu
mengidentifikasi
dan
mengungkapkan
gejala cemas.
b. Mengidentifikasi
,
mengungkapkan
a. Temani pasien
untuk
memberikan
keamanan dan
mengurangi
takut.
b. Berikan
informasi
faktual
mengenai
diagnosis,
tindakan
prognosis.
Menunjukkan
perhatian dan
keinginan untuk
membantu.
Membantu pasien
memahami tujuan
dari apa yang
dilakukan dan
mengurangi
masalah karena
ketidaktahuan.
18

dan
menunjukkan
teknik untuk
mengontol
cemas.
c. Vital sign dalam
batas normal.
d. Postur tubuh,
ekspresi wajah,
bahasa tubuh
dan tingkat
aktivitas
menunjukkan
berkurangnya
kecemasan.
c. Dorong pasien
untuk
mengungkapkan
perasaan,
ketakutan,
persepsi.
Ungkapan perasaan
dapat memberikan
rasa lega sehingga
mengurangi
kecemasan.
5. Risiko kekurangan
volume cairan
berhubungan dengan
pascaobstruksi
diuresis.
Tujuan :
Setelah dilakukan
perawatan selama
...x 24 jam klien
mampu
mempertahankan
keseimbangan
cairan tubuh.
Kriteria Hasil :
a. Mempertahanka
n urine output
sesuai dengan
usia dan BB, BJ
urine normal.
b. Tekanan darah,
nadi, suhu tubuh
dalam batas
a. Pertahankan
intake dan
output cairan.
b. Monitor vital
sign setiap
15menit – 1
jam.
c. Monitor status
hidrasi
( kelembaban
membran
mukosa, nadi
adekuat,
tekanan darah
Untuk
mengoptimalkan
keseimbangan
cairan.
Untuk mendeteksi
kekurangan
volume cairan.
Untuk mengetahui
setiap saat status
hidrasi.
19

normal
c. Tidak ada tanda
tanda dehidrasi,
elastisitas turgor
kulit baik,
membran
mukosa lembab,
tidak ada rasa
haus yang
berlebihan.
ortostatik ),
jika
diperlukan.
6. Risiko tinggi disfungsi
seksual berhubungan
dengan sumbatan
saluran ejakulasi,
hilangnya fungsi
tubuh.
Tujuan :
Setelah dilakukan
perawatan selama
...x 24 jam klien
mampu
mempertahankan
fungsi seksual.
Kriteria Hasil :
Klien akan
menyadari
keadaannya dan
akan mulai lagi
interaksi seksual
dan aktivitas secara
optimal.
a. Motivasi pasein
untuk
mengungkapkan
perasaannya
berhubungan
dengan
perubahannya.
b. Libatkan
keluarga/istri
dalam
perawatan
pemecahan
masalah fungsi
seksual.
c. Anjurkan pasien
untuk
menghindari
hubungan
seksual selama 1
bulan setelah
Memberikan
informasi untuk
membantu dalam
menentukan
pilihan atau
keefektifan
intervensi.
Memberikan
informasi untuk
membantu dalam
menentukan
pilihan atau
keefektifan
intervensi.
Menjamin
keamanan untuk
membantu
penyembuhan
pascaoperasi.
20

operasi.
21

DAFTAR PUSTAKA
Amalia, Rizki. 2010. Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Pembesaran Prostat Jinak.
Jurnal Unimus.
Birowo Ponco dan Rahardjo D. 2002. Pembesaran Prostat Jinak. Jurnal
Kedokteran & Farmasi Medika No 7 tahun ke XXVIII.
Brunner & Suddarth. 2001. Buku Ajar Medikal Bedah . Edisi 8 Volume 2. Jakarta:
EGC.
Dharmojo B, Martono H. 2000. Buku Ajar Geriatri (untuk kesehatan usia lanjut).
Edisi 2. Jakarta : FKUI.
Mansjoer, Arif. 2000. Kapita Selekta Kedokteran. Edisi 3. Jakarta: Media
Aesculapius.
Nursalam dan Fransisca B. 2009. Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan
Gangguan Sistem Perkemihan. Jakarta : Salemba Medika.
Pakasi, Ruland D N. 2009. Total Prostate Spesific Antigen, Prostate Spesific
Antigen Density and Histophatologic Analysis on Benign Enlargment of
Prostate. The Indonesian Journal of Medical Science Volume 1 No.5 July
2009 p. 263-274.
Price, Sylvia A, dkk. 2006. Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit.
Edisi 6 Volume 2. Jakarta : EGC.
Sjamsuhidajat, Wim de Jong. 2004. Buku Ajar Ilmu Bedah. Jakarta : EGC.
22