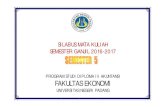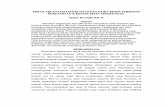Akuntansi Lingkungan Ta
-
Upload
hendra-mctop -
Category
Documents
-
view
15 -
download
1
description
Transcript of Akuntansi Lingkungan Ta

AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI PENUNJANG
KELANGSUNGAN PERUSAHAAN DAN ALAM
I. Pendahuluan
Perkembangan industri di era perekonomian modern ini
sungguh pesat. Perusahaan-perusahaan sudah semakin menjamur
dan mereka berlomba-lomba dalam memperoleh tingkat
provitabilitas yang tinggi dari kegiatan operasional mereka.
Perusahaan di dalam menjalankan kegiatannya memanfaatkan
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila
sumber daya yang dimanfaatkan berupa sumber daya alam yang
dilaksanakan secara besar-besaran , maka akan terjadi perubahan
ekosistem yang mendasar (Handayani, 2010). Fandeli (1995)
menyatakan bahwa agar kegiatan tersebut tidak menyebabkan
menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan
perencanaan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadi
dampak yang negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan
suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Hal
ini kemudian digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29
tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL). Peraturan ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 (Fandeli, 1995).
Dalam perekonomian modern seperti saat ini, walau
terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai lingkungan,
namun dampak dari pesatnya perkembangan ekonomi tetap
memunculkan berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan. Isu
tersebut dapat berupa pemanasan global, ekoefisiensi, dan
kegiatan industri lain yang memberi dampak langsung terhadap
lingkungan sekitarnya (Agustia, 2010). Polusi udara dan air,
kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, bahan kimia, hujan asam,
radiasi sampah nuklir, dan masih banyak petaka lain yang

menyebabkan stress mental maupun fisik terjadi karena kesalahan
di dalam alokasi sumber daya manusia dan alam yang di lakukan
oleh perusahaan sebagai penyebab utama (Capra, 1993 dalam
Sueb, 2001).
Perusahaan yang hanya memberikan perhatian pada
manajemen dan pemilik modal, kini harus melihat ke sisi baru
yakni tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder yang
telah menjadi topik sangat menarik dan semakin banyak dibahas,
hal ini berkaitan dengan adanya kesadaran suatu perusahaan atau
institusi untuk tidak hanya menghasilkan laba setinggi-tingginya,
tetapi juga bagaimana laba tersebut dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat (Pratiwi). Lanjut menurut Pratiwi, semakin
berkembangnya kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba
secara otomatis menimbulkan konsekuensi lingkungan hidup di
sekitarnya.
Salah satu jenis perusahaan adalah perusahaan manufaktur,
yang mengolah bahan baku atau bahan dasar menjadi barang jadi
yang siap dijual. Namun sering kali dalam kegiatan operasinya,
perusahaan manufaktur menghasilkan limbah yang tentu saja
dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Agustia (2010)
menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya inefisensi
dalam operasi perusahan tersebut. Konsep mengenai pengelolaan
lingkungan yang dipahami perusahaan adalah terbatas pada
pengelolaan limbah yang dihasikan dari proses produksi, tanpa
adanya pertimbangan untuk mengubah proses produksi agar
limbah yang dihasilkan dapat dikurangi (Agustia, 2010).
Menurut Fitriyani & Mutmainah (2011), keberadaan
perusahaan manufaktur di Indonesia dapat membangun sekaligus
merusak. Keberadaan perusahaan manufaktur apabila dipandang
dari sisi positifnya dapat menciptakan lapangan kerja sehingga
dapat membangun perekonomian masyarakat. Namun di sisi
negatif, keberadaan perusahaan manufaktur menghasilkan
buangan berupa limbah pabrik yang apabila tidak dapat dikelola

dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
Pencemaran ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan,
namun juga dapat menimbulkan penurunan kesejahteraan
masyarakat karena pada akhirnya masyarakatlah yang
menanggung beban akbiat pencemaran lingkungan.
Keadaan lingkungan khususnya di Indonesia sudah dalam
tahap yang sangat memprihatinkan, di mana terjadi kerusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran yang dihasilkan
oleh limbah hasil produksi berbagai perusahaan. Menurut Hilman
(2007), salah satu masalah lingkungan hidup yang sangat
memprihatinkan adalah pemanasan global (global warming).
Menurut Pratiwi, salah satu sumber penyebab terjadinya
pemanasan global yaitu akibat adanya eksploitasi alam yang
dilakukan oleh manusia tanpa pertanggungjawaban.
Permasalahan lingkungan juga semakin menjadi perhatian
yang serius, baik oleh konsumen, investor maupun pemerintah.
Investor asing memiliki kecenderungan mempersoalkan masalah
pengadaan bahan baku dan proses produksi yang terhindar dari
munculnya permasalahan lingkungan, seperti : kerusakan tanah,
rusaknya ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi suara
(Ja’far dan Arifah, 2006). Darwin (2007), melihat ada empat hal
alasan isu lingkungan semakin signifikan, yaitu :
1. Ukuran perusahaan yang semakin besar. Semakin besar
perusahaan, diperlukan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam
pembuatan keputusan berkaitan dengan operasi, produk dan
jasa yang dihasilkan.
2. Aktivis dan LSM bidang lingkungan hidup telah tumbuh
dengan pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Mereka
akan mengungkap sisi negatif perusahaan yang terkait dengan
isu lingkungan hidup dan akan menuntut tanggung jawab atas
kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang timbul oleh
operasi perusahaan.

3. Reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan saat
ini menyadari bahwa reputasi, merek, dan citra perusahaan
merupakan isu strategis bernilai tinggi dan harus dilindungi.
4. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat. Isu
lingkungan dan sosial yang berdampak negatif akan menyebar
dan dapat diakses dengan mudahnya menggunakan teknologi
informasi.
Banyaknya masalah yang timbul akibat aktivitas operasi
perusahaan menimbulkan dorongan bagi perusahaan untuk
melestarikan lingkungan, salah satunya dengan menerapkan
akuntansi lingkungan. Sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi
untuk pengambilan keputusan dan pertangungjawaban. Selama
ini, laporan keuangan hanya difokuskan kepada kepentingan
investor dan kreditor sebagai pemakai utama laporan keuangan,
tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya,
misalnya polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan
kerja, dan lainnya (Suaryana, 2011).
Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban memiliki fungsi
sebagai pengendali terhadap aktivitas setiap unit usaha
(Handayani, 2010). Tanggung jawab managemen tidak terbatas
pada pengelolaan dana dalam perusahaan, tetapi juga meliputi
dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan
sosialnya. Bentuk pertanggungjawaban akuntansi ini tentu saja
harus diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dengan
menyajikan dan mengungkapkan setiap materi akuntansi
informasi yang dibutuhkan (Handayani, 2010).
Pengungkapan akuntansi lingkungan di negara-negara
berkembang memang masih sangat kurang. Banyak penelitian
yang berkembang di area social accounting disclosure
memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja
lingkungannya masih sangat terbatas (Susilo, 2008). Lindrianasari
(2007) menegaskan bahwa salah satu faktor keterbatasan itu

adalah lemahnya sangsi hukum yang berlaku di negara tersebut.
Lindrianasari (2007) mengutip penelitian Mobus (2005) yang
menemukan bahwa terdapat hubungan yang negative antara
sangsi hukum pengungkapan lingkungan yang wajib dengan
penyimpangan aturan yang dilakukan oleh perusahaan.
Menurut Susilo (2008), praktik akuntansi lingkungan di
Indonesia sampai saat ini belumlah efektif. Berikut merupakan
penjelasan susilo mengenai hal tersebut.
Cepatnya tingkat pembangunan di masing-masing daerah
dengan adanya otonomi ini terkadang mengesampingkan
aspek lingkungan yang disadari atau tidak pada akhirnya
akan menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan
lingkungan. Para aktivis lingkungan di Indonesia menilai
kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini disebabkan
oleh ketidak konsistenan pemerintah dalam menerapkan
regulasi. Ketidakkonsistenan pemerintah misalnya
mengabaikan regulasi mengenai tata ruang. Kawasan yang
seharusnya menjadi kawasan lindung dijadikan kawasan
industri, pertambangan dan kawasan komersial lain. Tanpa
kontrol yang kuat dari pemerintah, potensi kerusakan
lingkungan akan semakin besar.
Bukti lain lemahnya penerapan akuntansi lingkungan di
Indonesia didukung oleh hasil penelitian Afdal (2012) yang
menyatakan bahwa hanya ada lima perusahaan yang berperingkat
emas dan hijau dari Program Penilaian Peringkat Kinerja
(PROPER) pada periode 2010-2011. Kurangnya jumlah ini dapat
menunjukkan lemahnya pengelolaan lingkungan termasuk
akuntabilitas lingkungan oleh perusahaan-perusahaan dan para
eksekutif bisnisnya (Afdal, 2012).
Apabila dilihat secara lebih mendalam, akuntansi
lingkungan sangat bermanfaat bagi perusahaan yang
menerapkannya, karena dapat membantu perusahaan dalam
meningkatkan provitabilitas dalam operasinya. Salah satu

contohnya adalah dapat meningkatkan harga pokok produksi yang
tentu saja dapat menutupi biaya yang berkaitan dengan
lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga dapat
mempengaruhi hubungan sosial antara perusahaan dengan
lingkungan alam maupun sosial sekitarnya, sehingga penerapan
akuntansi lingkungan dapat menguntungkan dari sisi ekonomi dan
sosial, namun sayangnya di Indonesia hanya beberapa perusahaan
yang menerapkan praktik akuntansi lingkungan.
Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk
memaparkan betapa pentingnya akuntansi lingkungan sebagai
penunjang keberlangsungan perusahaan dan pelestarian alam,
sehingga diharapkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
khususnya di Indonesia dapat meningkat dan membawa
keuntungan bagi perusahaan maupun bagi masyarakat dan alam
sekitarnya.
II. Pembahasan
II.1 Konsep Akuntansi Lingkungan
II.1.1 Definisi Akuntansi Lingkungan
Terdapat berbagai macam definisi mengenai akuntansi
lingkungan oleh para praktisi. AICPA (2004) dalam Volosin
(2008:3) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai :
“The identification, measurement, and allocation of
environmental costs¸the integration of these environmental
costs into business decisions, and the subsequent
communication of the information to a company’s
stakeholders”.
Artinya adalah akuntansi lingkungan merupakan
akuntansi yang di dalamnya terdapat identifikasi, pengukuran,
dan alokasi biaya lingkungan, di mana biaya-biaya lingkungan
ini diintegrasikan dalam pengambilan keputusan bisnis, dan

selanjutnya dikomunikasikan kepada para stakeholders.
Berdasarkan definisi green accounting di atas maka bisa
dijelaskan bahwa green accounting merupakan akuntansi yang
di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan
mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan (Aniela,
2012).
Djogo (2002) menyatakan bahwa akuntasi lingkungan
atau Environmental Accounting (EA) adalah istilah yang
berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan
(environmental costs) ke dalam praktek akuntasi perusahaan
atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak
(impact) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul
sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas
lingkungan. Sedangkan menurut Junus dalam Rossje (2006)
akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran dan
alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian
biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta
mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders
perusahaan. Lemanthe (dalam Rossje, 2006) memberikan
pendekatan akuntansi biaya lingkungan secara sistematis dan
tidak hanya berfokus pada akuntansi untuk biaya proteksi
lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan biaya lingkungan
terhadap material dan energi. Akuntansi biaya lingkungan
menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta
memastikan adanya efisiensi biaya dan diaplikasikan untuk
mengukur biaya kualitas dan jasa (Lemanthe, dalam Rossje
2006).
Menurut Environmental Accounting Guidelines dalam
Panggabean (2012), akuntansi lingkungan mencakup
pengidentifikasian biaya dan manfaat dari aktivitas konservasi
lingkungan, penyediaan sarana atau cara terbaik melalui
pengukuran kuantitatif, untuk mendukung proses komunikasi

agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memelihara
hubungan menguntungkan dengan komunitas serta meraih
efektivitas dan efisiensi dari aktivitas konservasi lingkungan.
Akuntansi lingkungan berbeda dengan akuntansi
konvensional. Rossje (2006) memaparkan perbedaan tersebut
sebagai berikut :
1. Akuntansi konvensional hanya memperhatikan kejadian
ekonomi, sedangkan akuntansi lingkungan memperhatikan
dampak kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan demi
kelangsungan hidup organisasi perusahaan.
2. Akuntansi konvensional tidak memiliki perhatian terhadap
transaksi-transaksi yang bersifat non reciprocal
transactions, tetapi hanya mencatat transaksi secara timbal
balik (reciprocal transactions). Sedangkan akuntansi
lingkungan mencatat transaksi yang bersifat tidak timbal
balik, seperti polusi, kerusakan lingkungan atau hal-hal
negatif dari aktivitas perusahaan.
3. Dalam sistem akuntansi lingkungan berorientasi pada flow
yang mendasarkan pada analisis sebab dan akibat secara
sistematis khususnya biaya yang terkait dengan output,
seperti emisi, pembuangan sampah dan limbah yang
dijadikan input perusahaan. Namun dalam akuntansi
konvensional, biaya-biaya tersebut diberlakukan sebagai
biaya overhead (factory overhead cost) dan dialokasikan
secara terpisah.
4. Sistem akuntansi lingkungan mengenal adanya potentially
hidden costs, contingent costs dan image and relationship
costs, sedangkan sistem akuntansi konvensional hanya
mengenal biaya-biaya yang melekat langsung pada produk.
a. Potentially hidden costs adalah biaya-biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu
produk sebelum proses produksi (misal : biaya desain
produk), biaya selama proses produksi (seperti biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya

overhead) dan backend environment cost (misal : lisensi
mutu produk).
b. Contingent cost adalah biaya yang mungkin timbul dan
mungkin tidak terjadi dalam suatu perusahaan dan
dibebankan pada contingent liabilities cost (contoh :
biaya cadangan untuk kompensasi kecelakaan yang
mungkin terjadi).
c. Image and relationship costs adalah biaya yang
dipengaruhi oleh persepsi manajemen, pelanggan,
tenaga kerja, publik dan lembaga pemerintah tentang
kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan dan
bersifat subyektif, contoh : pelaporan biaya lingkungan
secara sukarela oleh perusahaan.
5. Dalam akuntansi lingkungan dipertimbangkan private cost
dan societal cost dalam membuat keputusan, sedangkan
dalam akuntansi konvensional tidak mempertimbangkan
kedua biaya tersebut dalam pembuatan keputusan
perusahaan.
a. Private cost merupakan biaya yang terjadi dalam suatu
perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap
bottom line perusahaan.
b. Societal cost menggambarkan dampak biaya lingkungan
dan sosial dalam suatu entitas dan merupakan biaya
eksternal, contohnya adalah biaya yang dikeluarkan
sebagai dampak pencemaran lingkungan.
Aspek-aspek yang menjadi bidang garap akuntansi
lingkungan adalah sebagai berikut (Cahyono, 2002) :
1. Pengakuan dan identifikasi pengaruh negatif aktifitas bisnis
perusahaan terhadap lingkungan dalam praktek akuntansi
konvensional.
2. Identifikasi, mencari dan memeriksa persoalan bidang
garap akuntansi konvensional yang bertentangan dengan
kriteria lingkungan serta memberikan alternatif solusinya.

3. Melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun
inisiatif untuk memperbaiki lingkungan pada praktik
akuntansi konvensional.
4. Pengembangan format baru sistem akuntansi keuangan dan
nonkeuangan, sistem pengendalian pendukung keputusan
manajemen ramah lingkungan.
5. Identifikasi biaya-biaya (cost) dan manfaat berupa
pendapatan (revenue) apabila perusahaan lebih peduli
terhadap lingkungan dari berbagai program perbaikan
lingkungan.
6. Pengembangan format kerja, penilaian dan pelaporan
internal maupun eksternal perusahaan.
7. Upaya perusahaan yang berkesinambungan, akuntansi
kewajiban, resiko, investasi biaya terhadap energi, limbah
dan perlindungan lingkungan.
8. Pengembangan teknik-teknik akuntansi pada aktiva,
kewajiban dan biaya dalam konteks non keuangan
khususnya ekologi.
Rossje (2006) mengemukakan dua maksud
dikembangkannya akuntansi lingkungan, yaitu :
1. Akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen
Sebagai alat manajemen lingkungan akuntasi lingkungan
digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi
berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi
lingkungan. Data akuntasi lingkungan juga digunakan untuk
menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya
konservasi lingkungan keseluruhan dan juga investasi yang
diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain
itu akuntasi lingkungan juga digunakan untuk menilai
tingkat keluaran dan capaian tiap tahun untuk menjamin
perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus
menerus.

2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan
publik
Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi
lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif
lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya
kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap
akuntansi lingkungan dari para pihak, pelanggan dan
masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk merubah
pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan
lingkungan.
II.1.2 Biaya Lingkungan
Secara definisi biaya lingkungan adalah biaya yang
dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan.
Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal (berhubungan
dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi
dampak lingkungan) maupun eksternal (berhubungan dengan
perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan).
Sedangkan biaya perlindungan lingkungan meliputi biaya
pencegahan, pembuangan, perencanaan, pengendalian,
pengubahan, dan perbaikan lingkungan (Susenohaji, 2001).
Sumber-sumber biaya lingkungan menurut Rossje (2006)
meliputi sebagai berikut :
a. Biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat
limbah dan gas buangan (waste and emission treatment),
yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memelihara,
memperbaiki, mengganti kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh limbah perusahaan.
b. Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan
(prevention and environmental management) adalah
biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan mengelola
limbah untuk menghindari kerusakan lingkungan.

c. Biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produk
(material purchase value of non-product) merupakan
biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang bukan
hasil produksi dalam rangka pencegahan dan
pengurangan dampak limbah dari bahan baku produksi.
d. Biaya pengolahan untuk produk (processing cost of non-
product output) ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk pengolahan bahan yang bukab hasil produk.
e. Penghematan biaya lingkungan (environmental revenue)
merupakan penghematan biaya atau penambahan
penghasilan perusahaan sebagai akibat dari pengelolaan
lingkungan.
Biaya lingkungan terkait erat dengan lingkungannya.
Biaya ini meliputi antara lain; biaya degradasi tanah,
pencemaran lingkungan, biaya penyusutan air, biaya untuk
daur ulang, biaya untuk membayar denda, bunga, dan biaya
ganti rugi karena kerusakan lingkungan serta kehilangan flora
dan fauna. Selain itu, ada juga biaya lingkungan yang
cenderung tidak diketahui dengan jelas oleh pimpinan
perusahaan atau organisasi lain. Biaya ini cenderung
tersembunyi seperti biaya untuk persiapan asuransi,
pengendalian polusi, dan biaya untuk pengolahan limbah.
(Rossje, 2006).
Kerusakan lingkungan sebagai akibat aktivitas operasi
perusahaan memang seharusnya menjadi tanggung jawab
perusahaan yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya
perusahaan-perusahaan masih banyak yang tidak peduli akan
nasib lingkungan sekitarnya sehingga masyarakatlah yang
harus memikul dampak kerusakan lingkungannya. Rossje
(2006) memaparkan tiga macam biaya lingkungan yang timbul
dari dampak pencemaran lingkungan yang ditanggung oleh
masyarakat :

a. Damage Cost, yaitu biaya akibat dampak langsung dan
tak langsung dari limbah, misalnya meningkatnya
berbagai macam penyakit dan terganggunya reproduksi
makhluk hidup.
b. Avoidance Cost, biaya ekonomi dan sosial dalam
kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari
dampak pencemaran yang terjadi. Misalnya biaya untuk
penyaring udara.
c. Abatement Cost, yaitu biaya sumber daya yang
digunakan untuk melakukan penelitian, perencanaan,
pengelolaan dan pemantauan pencemaran.
Rossje (2006) melanjutkan bahwa terdapat empat
tingkatan biaya lingkungan dalam melakukan analisa full
costing, yaitu :
a. Usual Cost and Operating Cost
Usual cost adalah cost yang berkaitan langsung dengan
produk, termasuk biaya pembuatan, peralatan, material,
pelatihan, tenaga kerja dan energi.
b. Hidden Regulatory Cost
Merupakan biaya yang berkaitan dengan ketaatan
terhadap peraturan pemerintah seperti biaya pengujian,
monitoring dan inspeksi.
c. Contingent Liability Cost
Biaya yang berkaitan dengan kemungkinan kewajiban
perusahaan di masa yang akan datang seperti kerusakan
dan biaya perbaikan di masa yang akan datang.
d. Less Tangible Cost
Dengan mengurangi atau mengeliminasi pencemaran dan
merespon permintaan konsumen atas produk yang ramah
lingkungan, suatu perusahaan dapat merealisasikan Cost
Saving (less tangible cost) berupa naiknya revenue atau
menurunnya expense.
II.2 Manfaat Penerapan Akuntansi Lingkungan

Keberlangsungan aktivitas perusahaan tergantung oleh
banyak faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan tempat
perusahaan berdiri. Untuk itu diperlukan sebuah hubungan
timbal balik antara perusahaan dan lingkungan Perusahaan tak
akan mampu beroperasi dengan maksimal tanpa dukungan
lingkungan sekitar, dan perusahaan harus turut berkontribusi
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan
sebagai akibat aktivitas operasionalnya.
Perusahaan memerlukan dukungan dari stakeholders
seperti pemegang saham, pegawai, konsumen, kreditur,
supplier, pemerintah dan aktivis untuk dapat mencapai tujuan
jangka panjangnya. Dukungan untuk bisnis secara umum
tergantung pada kredibilitas penempatan stokeholders dalam
komitmen perusahaan. Kini stakeholder menginginkan kegiatan
perusahaan akan lebih menghargai kepentingan dan hal-hal
yang bermanfaat bagi mereka, dalam arti yang luas perusahaan
diminta untuk menentukan sikap etis dalam mencapai
kesuksesan (Debora & Ismail). Dharmayanti (2011) menyatakan
bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan
terhadap penilaian keberhasilan perusahaan, yaitu :
Urusan lingkungan
Dimulai dari masalah pencemaran udara yang berfokus pada
pipa asap pabrik yang menyebabkan iritasi pada masyarakat
sekitar pabrik. Selain pencemaran udara, yang harus
diperhatikan adalah pencemaran air.
Sensivitas moral
Berkaitan dengan tekanan publik akan adanya keadilan
dalam ketengakerjaan. Hal tersebut kini telah tercantum
dalam hukum, peraturan, kontrak dan kegiatan-kegiatan
perusahaan.
Penilaian buruk dan aktivis
Tekanan masyarakat atau kelompok tertentu menyerang
instansi dinilai buruk, seperti perusahaan Indorayon yang
diboikot karena membuang limbah dengan proses yang tidak
standar. Para investor berpandangan bahwa investasi

mereka seharusnya tidak hanya untuk mendapatkan
pendapatan namun juga untuk masalah-masalah etis.
Sinergi semua faktor dan penguatan institusional
Hubungan diantara semua faktor berdampak pada
ekspektasi publik terdapat masalah etika. Dimana akibatnya
masyarakatnya akan lebih sadar akan pentingnya kontrol
terhadap perilaku perusahaan yang tidak etis. Kesadaran
publik tersebut berimbas pada dunia politik, yang
menyatakan reaksinya dalam hal penyusunan hukum dan
peraturan. Hal tersebut akan mengakomodasi kesadaran
publik dalam proses penguatan institusi dan penegakan
hukum.
Untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan yang
berujung pada kerugian hingga pemboikotan perusahaan, serta
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas
produksi perusahaan, maka diperlukan penerapan akuntansi
lingkungan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa
akuntansi lingkungan merupakan praktek akuntansi yang
memasukkan biaya lingkungan untuk pengambilan keputusan.
Rossje (2006) mengemukakan empat alasan pentingnya
perusahaan untuk memikirkan pengalokasian biaya lingkungan,
yaitu besarnya jumlah yang akan terkena dampak akibat
kegiatan perusahaan, luasnya wilayah penyebaran dampak,
intensitas dan lamanya dampak berlangsung, dan banyaknya
komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
dan sifat kumulatif dampak. Dengan penerapan akuntansi
lingkungan, maka akan didapatkan beberapa manfaat yang
dapat meningkatkan kualitas perusahaan dan lingkungan.
Penerapan akuntansi lingkungan salah satunya dengan
dimasukkannya biaya lingkungan dalam penganggaran
perusahaan. Rossje (2006) menyatakan bahwa maksud
dimasukkannya biaya lingkungan dalam penyusunan anggaran
adalah :

a. Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
dimana perusahaan akan mengumpulkan informasi tentang
lingkungan termasuk pencemaran dan kerusakan
lingkungan serta jalan keluar dalam mengatasi persoalan
ini.
b. Sebagai alat untuk mengukur kinerja manajer, karena
dengan dimasukkannya biaya lingkungan dalam biaya
produksi (anggaran perusahaan) maka dapat mencerminkan
biaya yang akurat atas suatu produk, agar dapat diketahui
laba bersih yang sesungguhnya yang menjadi hak
perusahaan tanpa harus dikaitkan dengan masalah
kerusakan lingkungan di kemudian hari.
c. Dengan menetapkan biaya lingkungan dalam anggaran
perusahaan secara dini, maka perusahaan akan lebih
berhati-hati terhadap lingkungan dan kalaupun pencemaran
tersebut masih tetap terjadi volumenya akan relatif kecil,
karena bagaimanapun juga perusahaan berharap agar biaya
lingkungan yang telah dianggarkan tidak dimanfaatkan
secara keseluruhan, namun ada penghematan atas biaya
lingkungan.
d. Dengan menetapkan biaya lingkungan dalam anggaran
perusahaan, maka perusahaan sudah memikirkan alat mana
yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah, sehingga
limbah yang dihasilkan limbah tersebut dapat didaur ulang.
Dalam hai ini perusahaan akan memperkirakan bahwa
minimal limbah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat
dan hasil penjualan limbah tersebut dapat menutupi biaya
lain-lain yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.
Contoh nyata dari perusahaan yang memasukkan biaya
lingkungan ke dalam penganggaran perusahaan adalah PT
Timah (Persero). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Panggabean dan Deviarti (2012), dalam rangka pemeliharaan
lingkungan PT Timah menganggarkan Rp 5.674.614.500,00
untuk biaya pengelolaan lingkungan. Selain itu, perusahaan

mengupayakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)
yang berkesinambungan, perusahaan telah mengalokasikan
sebagian dananya khusus untuk aktivitas-aktivitas sosial
tersebut. Panggabean dan Deviarti melanjutkan bahwa
perusahaan menyiapkan anggaran pada tahun 2009, sekitar Rp
26,6 miliar untuk pelaksanaan program CSR yang merupakan
dana yang wajib dicadangkan bagi perusahaan yang
memanfaatkan sumber daya alam (SDA).
Penerapan akuntansi lingkungan sangat bermanfaat bagi
perusahaan dan lingkungan. Berikut ini merupakan penjelasan
dari beberapa manfaat lainnya dari penerapan akuntansi
lingkungan.
II.2.1 Pembentukan Citra Positif Perusahaan
Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, citra didefinisikan
sebagai a picture of mind, yaitu suatu gambaran yang ada di
dalam benak seseorang. Citra dapat berubah menjadi buruk
atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak didukung oleh
kemampuan atau keadaan yang sebenarnya (Dahlan, 1992).
Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan membawa
manfaat bagi perusahaan, salah satunya citra positif di
masyarakat sekitar. Penyisihan biaya untuk pelestarian
lingkungan terkait sekali dengan citra PT Timah yang cukup
baik, hingga masyarakat setempat menyatakan bahwa PT timah
adalah bagian dari kehidupan mereka (Panggabean dan
Deviarti, 2012). Citra perusahaan adalah sebuah hal yang
sangat penting karena perusahaan yang memiliki citra negatif
tidak akan dapat melakukan operasi jangka panjang sebagai
akibat dari penolakan masyarakat yang berujung pada
penutupan perusahaan.
II.2.2 Peningkatan Kualitas Lingkungan

M. Alwi Dahlan, Paper: Peranan dan Peluang Pulic Relations dalam meningkatkan Citra
dan Pelayanan Perbankan, (disampaikan pada seminar PR Bank: Pasca UU Perbankan
1992 di Jakarta, 20 Juni 1992)